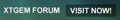Ahh, sementara saya… apa saya akan siap?
Saya kira, dibandingkan para ibu yang saya kagumi itu, keimanan saya mungkin berada jauh di anak tangga paling rendah. Buktinya pertanyaan itulah yang pertama terloncat dari mulut saya.
Syukurlah kondisi ananda baik.
Seorang suster menggendong satu sosok mungil setengah telanjang, hanya dibalut kain bedong seadanya dan menyodorkannya agar saya bisa melihat lebih jelas.
Putih kemerahjambuan, montok. Matanya yang terpejam terlihat sipit. Bibir mungilnya berbentuk segitiga sempurna. Seorang bayi perempuan!
Subhanallah…
Sulit bagi saya melukiskan perasaan, tapi setiap Ibu akan mengerti.
Hari pertama menjadi ibu.
Hari pertama ketika menerima hadiah terbaik yang Allah limpahkan kepada setiap perempuan.
Karunia yang di kemudian hari menjadi sumber kekuatan bagi setiap istri ketika merasa begitu lemah dan linglung mencari pegangan. Sumber dari semua keceriaan, di saat hati diam-diam menangis.
Jadi, sungguh saya tidak mengerti bagaimana bisa seorang perempuan menolak kodratnya menjadi seorang ibu, dan menolak anugerah yang diberikan Tuhan?
Perempuan Istimewa di Hati Abah Agil
“Ibu talalu barsi dan ikhlas untuk beta. Jadi Aba seng bisa ganti dengan orang lain. ” (“Ibu terlalu bersih (menjaga kehormatannya) dan ikhlas untuk saya, Saya tidak mungkin menggantikannya dengan orang lain. Nak.”) (Aba Agil, di ruang tengah rumah kami)
Sudah cukup lama saya pesimis dengan kesetiaan laki-laki. Sebagian besar kisah yang saya tuangkan di sini rasanya cukup memberikan gambaran bagi sa ya, betapa tipisnya kesetiaan lelaki zaman sekarang.
Kadang saya berpikir, lagi-lagi dengan pesimis, berapa lamakah waktu yang diperlukan lelaki untuk siap menikah lagi, setelah istri mereka berpulang?
Ini mungkin lahir dari sentimentil saya. Sebab saya tahu, dalam agama, bahkan dibenarkan bagi lelaki untuk menikah lagi ketika istri masih hidup (poligami), apalagi jika istri sudah tidak ada? Sama sekali tidak diperlukan batasan waktu untuk itu.
Barangkali karena saya perempuan yang besar dengan kisah-kisah cinta dunia yang abadi. Taj Mahal, Romeo dan Juliet, dan banyak lagi, hingga merasa secara pribadi penting menyoalkan hal ini.
Hingga suatu hari, saya kedatangan seorang pengarang muslimah yang saya kagumi semangat dan kejujuran tulisannya. Ida Azuz, muslimah asli Ambon ini mengomentari pernikahan kedua seorang ustadz terkenal yang ketika itu menjadi berita yang mengguncang banyak pihak.
“Yang jelas, pernikahan beliau membuat saya makin bangga dengan ayah saya, Mbak Asma.”
Ida Azuz lalu menceritakan sosok Aba Agil, ayahnya…
dan kisah cinta yang terus ingin dikenang lelaki itu hingga maut datang. Begitu menyentuh hingga saya memintanya untuk membagi kisah tersebut, sambil berharap semoga kisah terakhir ini menjadi catatan akhir yang indah, di hati sesama istri.
–o0o–
Gelegar suara Aba Agil pada saya ketika sarapan pagi membuat saya mengerut ketakutan. Memang hanya dua kata yang dikeluarkannya, tetapi saya benar-benar takluk.
Saya benar-benar tidak berdaya dibuatnya. Saya ketakutan.
Saya benar-be nar tidak siap dengan reaksi keras atas permintaan yang saya sampaikan dengan penuh ketulusan.
Padahal untuk menyampaikan permintaan itu, saya menyusun kata-kata sejak semalam agar tidak menyinggung perasaan Aba.Tetapi gelegar suara itu belum cukup, dengan satu gerakan cepat, Aba langsung meninggalkan meja makan, masuk ke kamar dan menguncinya dengan suara yang keras.
Seumur-umur saya baru sekali ini melihat Aba marah demikian keras. Apalagi kami masih berada dalam suasana duka karena Ibu berpulang baru dua bulan yang lalu.
Kemarahan yang keras di meja makan kemudian meninggalkan meja makan dalam kultur kami merupakan hal yang sangat jarang kami lakukan. Jika itu terjadi, pertanda kemarahan telah menghampiri batas-batasnya.
Dan itu saya dapatkan dari Aba Agil di pagi hari. Terus terang saya tidak siap.
Aba lalu mengunci diri di kamar. Dengan perasaan takut, saya menunggu Aba untuk makan siang. Sejam dua jam berlalu, Aba tidak mau keluar dari kamar. Kali ini Aba betul-betul marah pada saya. Padahal yang saya sampaikan itu menurut pandangan kami, anak-anak Aba, adalah untuk kebaikan Aba juga.
Apa yang saya sampaikan sebetulnya atas usul ustadz Agung Wirawan setelah mengetahui bahwa Aba masih dirundung sedih karena ditinggal Ibu dua bulan yang lalu.
Ustadz Agung mengatakan pada saya, sebaiknya kami membicarakan secara baik-baik pada Aba, untuk mencari pengganti Ibu di sisi Aba.
Ini sebetulnya awal kemarahannya itu pada saya. Dua bulan setelah ibu berpulang, saya melihat Aba seperti kehilangan semangat hidup. Kerap Aba duduk di teras rumah memandang jauh, dan dengan gerakan yang samar, mengelap matanya yang mulai berair. Saya juga sering mendapati Aba selesai shalat malam, duduk berdoa sambil menangis. Ah, di manakah semua ketabahan dan ketegaran yang Aba miliki itu?
Kami, anak-anaknya, berupaya keras bergantian menghibur Aba dari duka yang mendalam itu. Saya memahami kedukaannya itu dengan baik. Saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa ketika Ibu berada pada saat-saat kritis dalam hidupnya, ketika Ibu berdiri di ujung lekukan kehidupan dunianya, Aba, lelaki yang membuat Ibu semakin paham agama itu, justru tidak sempat membisikkan kalimat-kalimat pe ngantar untuk berpulang keharibaan Allah. Ketidakhadiran Aba di samping ibu pada saat saat terakhirnya ternyata membuat Aba terpukul.
Saya masih ingat, sehari sesudah Ibu kami tidurkan di tanah merah berliat Sudiang (Lokasi pemakaman di Makassar), Aba baru tiba dari Ambon. Saya menjemputnya di pelabuhan kapal, karena tidak mungkin menggunakan pesawat secara bebas dalam suasana konflik di Ambon.
Saya dan Aba bertemu pandang di pelabuhan, kami tidak berkata-kata, saya hanya menggelengkan kepala. Saya ingin mengirim isyarat bahwa perempuan yang kami cintai telah berpulang. Lidah saya kelu untuk mengucapkan kata-kata kepulangan itu. Terlalu sakit bagi saya. Sesaat kami bersitatap, Aba memeluk saya erat-erat, lalu saya mendengar nafas Aba yang berat. Ada yang basah di bahu saya.
Dua bulan telah berlalu. Saya masih menangkap kelabu di mata Aba. Aba lebih suka menyendiri atau tidur menghadap dinding. Sebagai anak, saya tahu, mata aba pastilah sudah basah. Kesedihan Aba tetap menggantung di matanya. Lalu saya bertemu dengan ustadz Agung Wirawan yang kenal baik dengan keluarga kami. Ustadz Agung menanyakan kabar Aba. Dan saya menyampaikan kalau Aba masih berat ditinggalkan Ibu. Dan meluncurlah usulan untuk mencarikan pengganti Ibu bagi Aba. Kata ustadz Agung, memang anak bisa merawat Aba dengan baik, tetapi beda dengan kehadiran seorang istri di samping.
Ini bukan saja berkaitan dengan persoalan fisik, tetapi secara mental, Aba butuh pendamping. Urai ustadz Agung.
Meskipun saya anak tertua, tetapi untuk hal-hal begini, saya perlu berunding dengan adik-adik saya. Kami sepakat untuk mencarikan pengganti Ibu. Tiba-tiba ada kesedihan yang menyergap kami saat berunding. Kami sedih sekali ketika menyadari ada orang lain yang akan mengantikan posisi ibu. Fidaan, si bungsu, mengatakan tidak mungkin orang lain bisa menempati tempat Ibu di hati kami. Tetapi untuk menemani Aba, apa boleh buat,kami harus mencari orang lain.